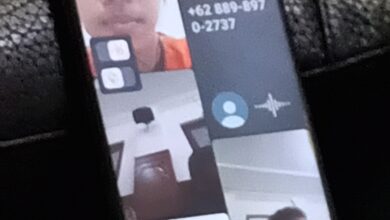Sidang KDRT Psikis Selebgram Vinna Natalia: Dari Pelapor Dugaan Kekerasan ke Kursi Terdakwa

Surabaya, LintasHukrim – Perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menyeret selebgram Vinna Natalia Wimpie Widjoyo, S.E. menghadirkan dinamika hukum yang tidak lazim. Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (17 November 2025), Vinna, yang merupakan istri dari pelapor, justru duduk sebagai terdakwa dalam perkara dugaan kekerasan psikis.
Sidang yang dipimpin Ketua majelis Hakim, S. Pujiono, SH, MH jaksa penuntut umum SISKA CHRISTINA, S.H., M.H . dan M.MOSLEH RAHMAN, SHdari Kejaksaan Negeri Surabaya, mengagendakan pemeriksaan keterangan terdakwa.
Dalam keterangannya, Vinna menjelaskan bahwa ia menikah pada 2012 dan dikaruniai tiga anak. Pernikahan yang dilangsungkan di Gereja Yohanes itu, menurutnya, sejak lama diwarnai kekerasan fisik dan psikis yang berulang.
Peristiwa yang disebut sebagai puncak konflik terjadi pada 12 Desember 2023. Vinna mengaku mengalami pemukulan oleh suaminya hingga menyebabkan trauma mendalam. Tiga hari kemudian, tepatnya 15 Desember 2023, ia meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya di Sidoarjo.
“Saya dihajar dari ujung kepala sampai ujung kaki,” ujar Vinna di hadapan majelis hakim.
Atas kejadian tersebut, Vinna lebih dulu melaporkan sang suami ke Polrestabes Surabaya atas dugaan KDRT. Namun, proses penanganan perkara berjalan lama. Di tengah proses itu, ia mengaku diarahkan oleh pihak kepolisian dan penasihat hukumnya saat itu untuk menempuh jalur perdamaian.
Dalam skema perdamaian tersebut, Vinna menyebut diminta mencabut laporan KDRT dan gugatan cerai. Sebagai kompensasi, dijanjikan uang Rp2 miliar, uang bulanan Rp75 juta, serta sebuah rumah senilai Rp5 miliar. Fakta yang kemudian menjadi pokok persoalan, kompensasi itu tidak diterima secara utuh.
“Uang bulanan hanya diberikan satu kali, sedangkan rumah sampai sekarang tidak ada,” kata Vinna.
Meski perdamaian telah ditempuh, Vinna mengaku tidak kembali ke rumah karena masih mengalami ketakutan dan trauma. Keputusan tersebut kemudian menjadi dasar pelaporan balik oleh sang suami, yang menuding Vinna melakukan kekerasan psikis karena dianggap telah menerima kompensasi namun menolak rujuk.
Sejak meninggalkan rumah, Vinna juga mengaku mengalami pembatasan akses terhadap anak-anaknya. Ia menyebut tidak diizinkan bertemu, bahkan pihak sekolah anak-anak menerima surat yang melarang pertemuan tanpa persetujuan suaminya.
Dalam persidangan, Vinna turut mengungkap dugaan kekerasan lain yang terjadi setelah perdamaian, termasuk dugaan pemukulan terhadap asisten rumah tangga menggunakan tongkat golf serta dugaan perselingkuhan.
Peristiwa-peristiwa tersebut, menurutnya, menjadi alasan ia kembali mengajukan gugatan cerai pada 2024.
Saat diperiksa penasihat hukum, Vinna merinci kekerasan yang ia alami pada 12 Desember 2023, mulai dari pemukulan, penarikan rambut, cekikan, diinjak agar tidak bisa melarikan diri, hingga dipukul menggunakan ikat pinggang.
“Dia mengatakan bisa membunuh saya,” ucap Vinna. Ia menambahkan bahwa selama pernikahan, kekerasan fisik kerap disertai kekerasan verbal berupa makian yang berlangsung bertahun-tahun.
Terkait proses restorative justice, Vinna menegaskan bahwa perdamaian bukanlah kehendaknya sepenuhnya. Ia mengaku berada dalam posisi tertekan dan tidak memiliki banyak pilihan. Sementara angka Rp20 miliar yang sempat muncul dalam proses mediasi di kejaksaan, menurutnya, merupakan perhitungan kewajiban yang belum dipenuhi, bukan angka kompensasi yang benar-benar diterima.
Perkara ini kini menempatkan Vinna dalam posisi paradoksal: seorang istri yang sebelumnya melaporkan dugaan KDRT, namun kemudian dilaporkan balik dan didudukkan sebagai terdakwa PKDRT psikis karena memilih tidak kembali ke rumah pasca-perdamaian.

Pada Rabu (15 November 2025), persidangan menghadirkan saksi ahli pidana dan saksi ahli psikologi yang diajukan oleh pihak terdakwa.
Perkara ini menjadi sorotan karena berangkat dari relasi rumah tangga yang kompleks. Vinna merupakan istri dari pelapor, yang melaporkannya atas dugaan PKDRT psikis.
Namun sebelum laporan tersebut dibuat, Vinna lebih dahulu melaporkan sang suami atas dugaan KDRT, sehingga posisi para pihak kerap dipersepsikan berbalik arah.
Dalam persidangan terungkap, laporan terhadap Vinna berangkat dari dalih bahwa ia telah menerima kompensasi rumah tangga, namun tetap memilih tidak kembali ke rumah. Fakta yang kemudian dipersoalkan, kompensasi tersebut tidak diterima secara utuh, baik dari sisi jumlah maupun realisasinya.
Saksi ahli pidana yang dihadirkan terdakwa menjelaskan bahwa ingkar janji atau kegagalan rujuk dalam rumah tangga tidak serta-merta dapat dipidana. Menurutnya, hukum pidana memiliki batas tegas dan tidak dapat digunakan untuk menarik konflik domestik ke ranah pidana tanpa terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum yang jelas, disengaja, dan dapat dibuktikan secara objektif.
“Tidak setiap kekecewaan atau konflik relasi dapat dimaknai sebagai tindak pidana,” jelas ahli di hadapan majelis hakim. Ia menegaskan bahwa penggunaan hukum pidana harus menjadi ultimum remedium, bukan alat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga yang bersifat personal.
Sementara itu, saksi ahli psikologi menyoroti karakter kekerasan psikis yang berbeda dengan kekerasan fisik. Kekerasan psikis merupakan bentuk kekerasan yang paling sulit dibuktikan karena tidak kasat mata dan tidak dapat disimpulkan dari satu peristiwa tunggal. Ahli menegaskan bahwa penilaian kekerasan psikis harus didasarkan pada pola perilaku yang berulang, konsisten, berdampak nyata pada kondisi psikologis korban, serta didukung pemeriksaan dan alat ukur psikologis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Selain itu, saksi ahli pidana juga menyinggung mekanisme restorative justice (RJ) yang sempat ditempuh para pihak. Ahli menjelaskan bahwa kesepakatan dalam RJ bukan sekadar kesepakatan moral, melainkan memiliki konsekuensi hukum bagi para pihak yang menyetujuinya.
Menurut ahli, ingkar janji terhadap kesepakatan RJ pada prinsipnya dapat menimbulkan implikasi hukum, termasuk potensi pidana, sepanjang terpenuhi unsur kesengajaan, adanya kerugian nyata, serta pelanggaran terhadap isi kesepakatan yang disetujui secara sadar oleh para pihak. Namun, penilaian tersebut tidak dapat dilakukan secara otomatis dan harus diuji secara cermat.
Ahli juga mengingatkan bahwa restorative justice bukanlah formalitas untuk menghindari proses hukum, melainkan mekanisme penyelesaian perkara yang menuntut itikad baik, keterbukaan, dan tanggung jawab dari semua pihak. Setiap dugaan pelanggaran terhadap kesepakatan RJ tetap harus dinilai secara objektif, proporsional, dan berdasarkan fakta hukum, bukan semata-mata asumsi atau kekecewaan sepihak.
Lebih lanjut, ahli psikologi menekankan bahwa permintaan perceraian atau keputusan seorang istri untuk tidak kembali ke rumah bukanlah indikator awal kekerasan psikis. Dalam banyak kasus, tindakan tersebut justru dapat menjadi respons atas relasi yang sudah tidak sehat atau konflik yang berkepanjangan.
Dalam keterangannya, Vinna Natalia menyatakan bahwa keputusannya untuk tidak kembali ke rumah bukan bertujuan melukai atau menekan kondisi psikis suami, melainkan sebagai bentuk perlindungan diri di tengah konflik rumah tangga yang terus berulang. Ia menegaskan bahwa sebelumnya telah melaporkan dugaan KDRT yang dialaminya.
Perkara ini memperlihatkan bagaimana konflik rumah tangga dapat berkembang menjadi proses pidana dengan narasi yang saling berhadapan, di mana satu pihak yang semula berposisi sebagai pelapor kemudian duduk sebagai terdakwa.
Majelis hakim akan melanjutkan persidangan dengan agenda tuntutan sebelum menentukan apakah rangkaian peristiwa tersebut memenuhi unsur kekerasan psikis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT, atau merupakan konflik rumah tangga yang berkembang menjadi perkara pidana.